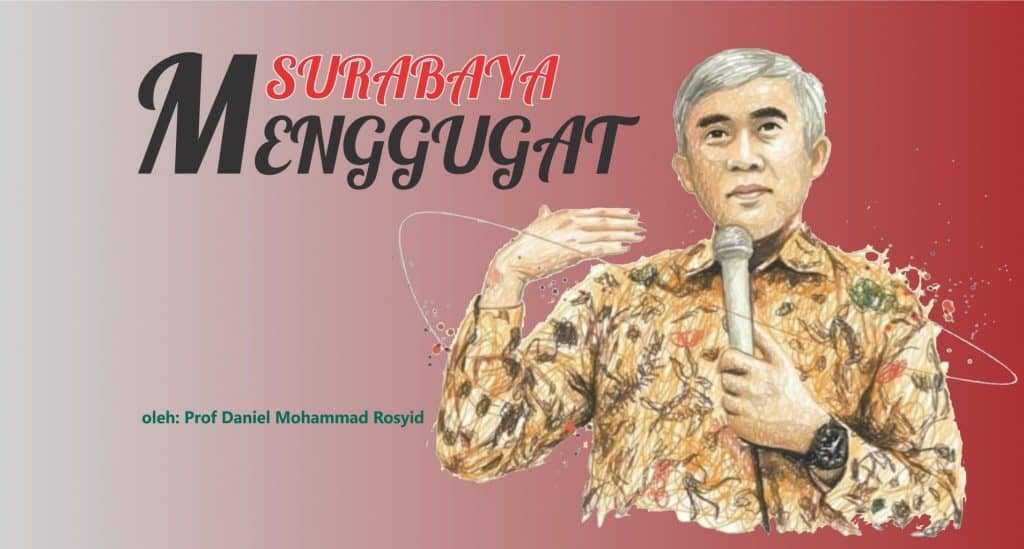Sekadar dipakai untuk “public relation”, tokohtokoh masyarakat sipil dari sektor agama dan kebudayaan juga memperkuat barisan “the middle ground” ini. Pluralisme adalah umpan politik yang dengan mudah dilahap barisan ini, karena kekuasaan memiliki seluruh perangkat untuk memaksimalkan kecemasan “kaum minoritas”. Setiap kali terjadi konflik sosial, pemerintah datang dengan solusi moral: kumpulkan pemuka agama.
Toleransi menjadi proyek ideologis negara, kendati dalam pengertian yang sangat sempit, yaitu sekadar toleransi di antara umat beragama. Bahwa sumber ketegangan sosial itu adalah disparitas dan kesalahan kebijakan pemerintah, tak ingin diakui.
Esensi Kritik Kritik adalah evaluasi pikiran terhadap realitas, yaitu mengurai inkonsistensi kebijakan. Inkonsistensi dalam kebijakan pertama-tama harus dimulai dengan memeriksa inkoherensi dalam ide. Karena itu fungsi kritik adalah mengurai, bukan membangun. Itulah tugas utama akademisi.
Jadi, tuntutan agar kritik itu harus “yang membangun” adalah tuntutan dari mereka yang tak ingin dikritik. Hakikat kritik adalah menunjukkan kesalahan, bukan memperbaikinya. Adalah tugas yang dikritik untuk memperbaiki konsepnya.
Dalam urusan publik, tugas si pejabat publik untuk memperbaiki kebijakan, karena ia digaji rakyat untuk itu. Demokrasi hidup dengan kritik. Tugas oposisi sudah dimulai sejak presiden dilantik. Karena itu, ide mengganti presiden memang melekat pada tugas oposisi. Itu bukan saja konstitusional, tapi memang logis: sungguh dungu bila oposisi berniat tidak mengganti presiden. Karena itu, mengaktifkan oposisi, justru menjamin kekuasaan tidak menempuh tradisi primitifnya: pongah.
Lalu, apakah kita pesimistis dengan keadaan? Tak perlu dijawab, karena politik bukan klinik psikologi. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi psikologi dari kaum terdidik yang justru menjadi pemuja kekuasaan.
Dalam isu mutakhir hari ini, yaitu tentang usulan agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan soal terorisme, pendukung utama usulan ini adalah justru kalangan terdidik dan aktivis masyarakat sipil pro pemerintah. Sungguh absurd bahwa kebijakan yang akan melemahkan demokrasi, justru dibela oleh kalangan yang mengerti hakikat demokrasi: bahwa tak sekali-kali mengizinkan penguasa memutuskan atas kehendak sendiri, aturan yang potensial membatalkan demokrasi.
Di depan kekuasaan, para tokoh masyarakat sipil patuh karena fanatisme. Kalangan terpelajar patuh karena kekurangan pikiran. Dan merekalah yang kini menyelenggarakan public relations pemerintah. Ajaib, tapi itulah sinopsis politik kita setelah 20 tahun reformasi: surplus fanatisme, defisit akal. [21 Mei 2018].
Lanjutkan ke Tulisan 1: Meme Pembubaran HTI